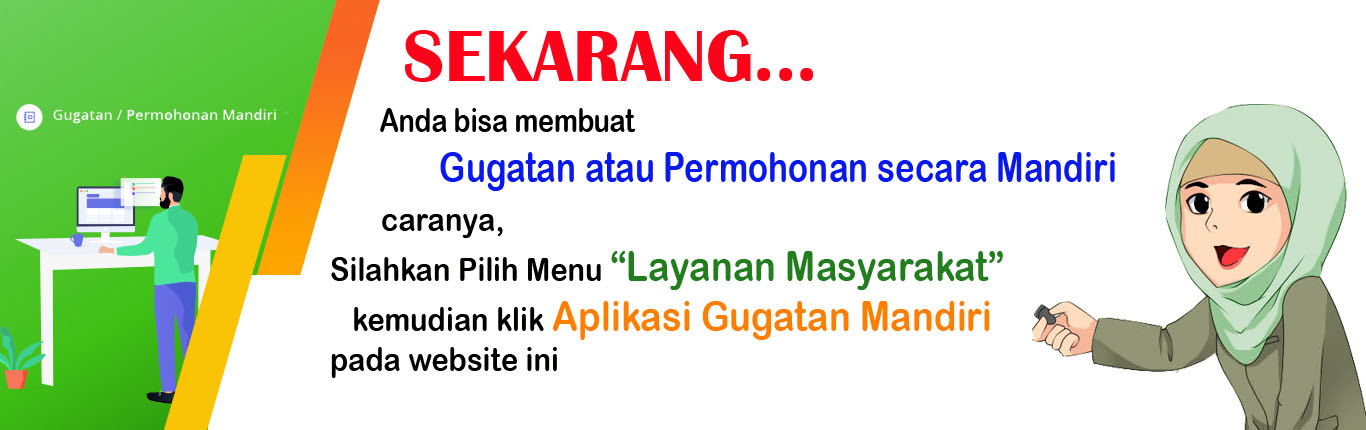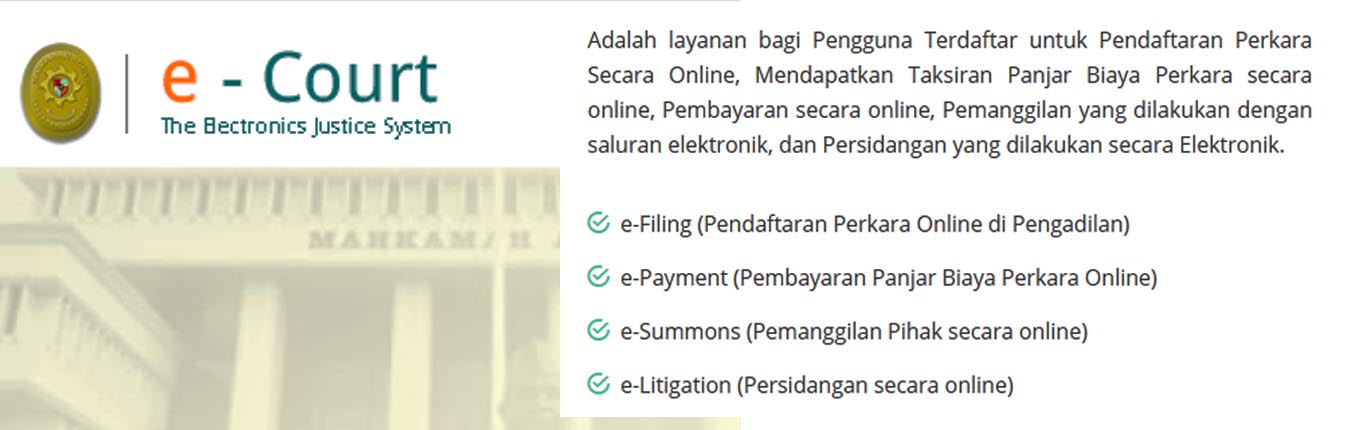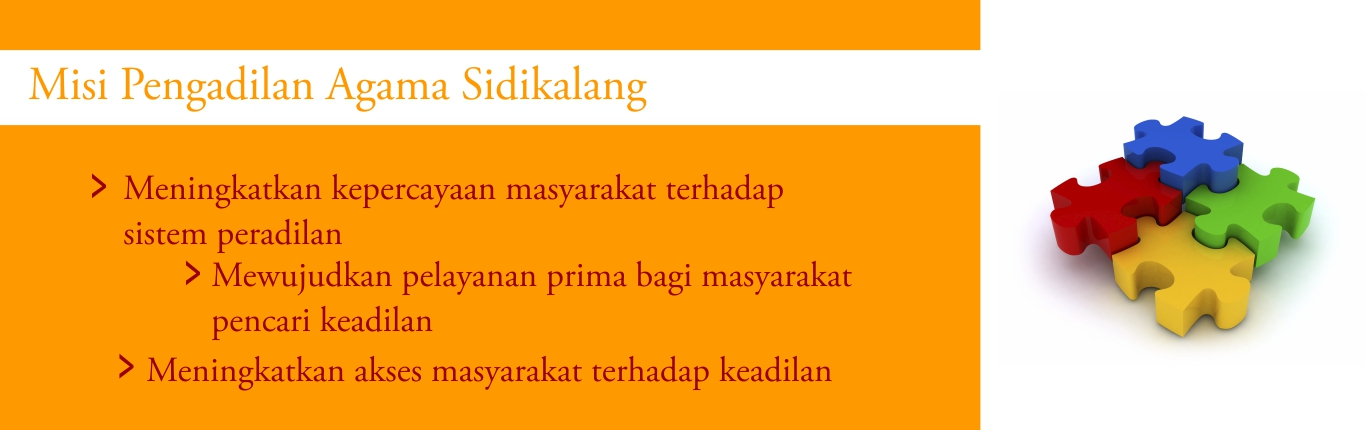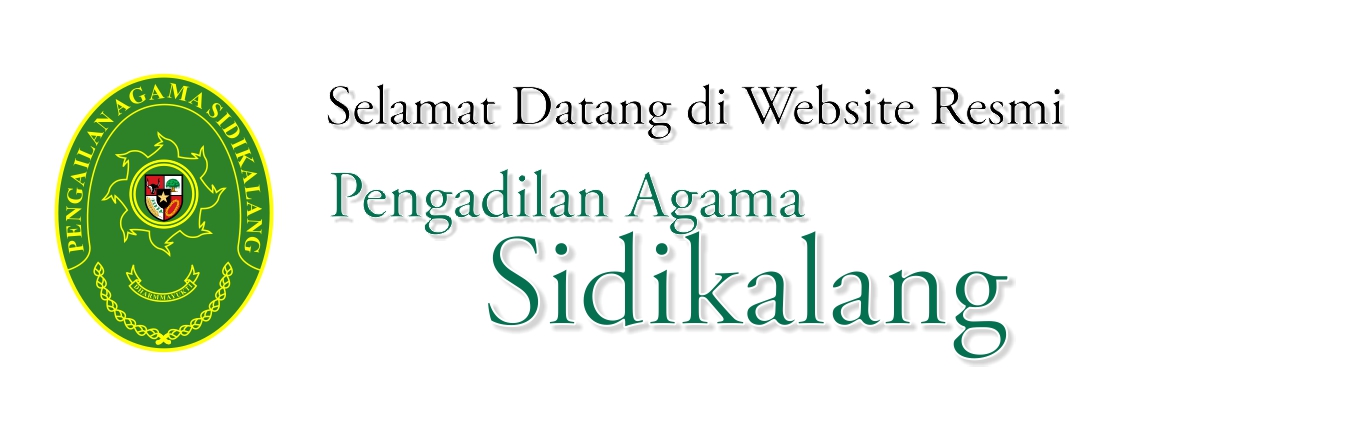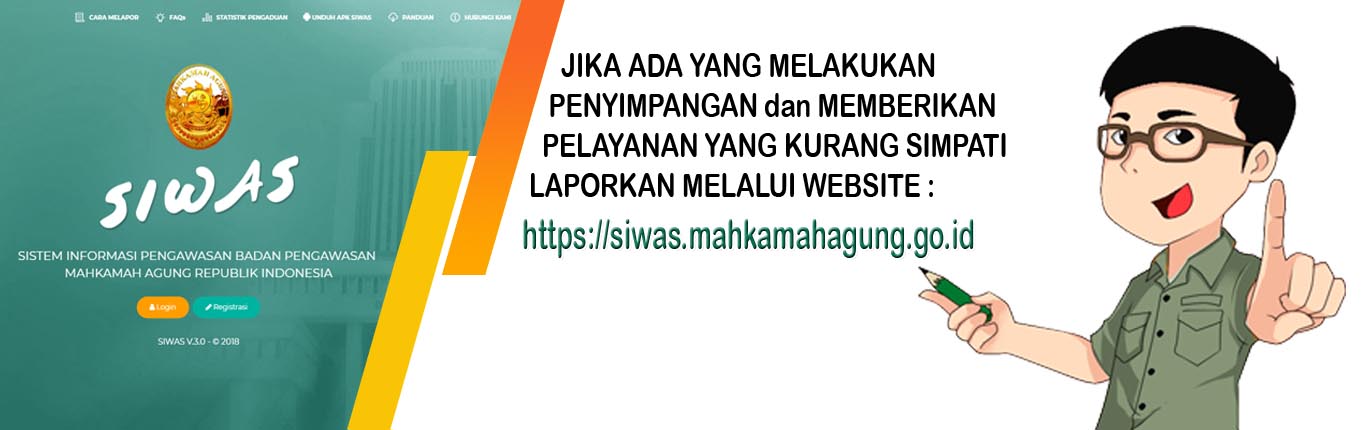![]()
| Prosedur Berperkara | Layanan Informasi | Jadwal Sidang | SIPP | APM |
| SIWAS MA RI | e - Court | Sukamas | Pelita | Validasi Akta Cerai |
| siMUPLI | Pojok | Kotak Kemajuan | SIGOA-SKM | SIYANTIS |
| Cuti Tahunan | Izin Keluar Kantor | Apl Gugatan Mandiri | SURTI - SURVEI BADILAG |

Hak atas tanah di Indonesia diatur pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut sebagai “UUPA”). Adapun hak-hak atas tanah di Indonesia terbagi menjadi berikut:[1]
- Hak Milik
- Hak Guna Usaha
- Hak Guna Bangunan
- Hak Pakai
- Hak Sewa
- Hak Membuka Tanah
- Hak Memungut Hasil Hutan
- Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang Undang serta hak hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53
Selain itu terdapat pula hak hak atas tanah lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Salah satu contohnya ialah Hak Pengelolaan yang diatur pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan. Hak Pengelolaan berbeda dan juga bukan merupakan bagian dari Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai sebagaimana diatur dalam UUPA.
Namun seiring dengan perkembangan hukum dewasa ini, terdapat beberapa tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan.[2] Terjadinya Hak Guna Bangunan dapat berdiri di atas hak lainnya:
- Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara
Tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat, dan/atau bukan merupakan asset barang milik negara/barang milik daerah.[3] Hak Guna Bangunan dapat berdiri di atas tanah negara. Hak Guna Bangunan ini diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.[4]
- Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengelolaan
Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.[5] Kewenangan yang dilimpahkan itu adalah kewenangan berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.[6] Pemegangnya dapat merencanakan penggunaan tanah yang bersangkutan dan menunjuk Badan Hukum atau orang yang diberi hak untuk menggunakannya dengan sesuatu hak atas tanah tertentu sesuai UUPA, misalnya Hak Guna Bangunan. Oleh karena itu seluruh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hak guna bangunan pada umumnya berlaku pula bagi hak guna bangunan diatas tanah hak pengelolaan sepanjang penggunaannya setiap pemegang hak guna bangunan tetap terikat pada syarat yang ditentukan dalam perjanjian pemberian penggunaan tanah antara pemegang hak pengelolaan dengan pemegang hak guna bangunan.[7] Berdasarkan hal tersebut maka Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan dapat dijadikan jaminan hak tanggungan, dimana HGB tersebut dijaminkan dalam bentuk Hak Tanggungan yang diberikan melalui Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), melalui 2 (dua) cara, yaitu:[8]
- Diberikan secara langsung oleh pihak yang berwenang[9]. Dimana pemberian hak tanggungan tersebut dibuat dalam bentuk APHT oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Diberikan secara tidak langsung melalui Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)[10]
Keputusan mengenai pemberian Hak Guna Bangunan diberikan oleh Menteri berdasarkan persetujuan pemegang hak pengelolaan.[11] Hak guna bangunan ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.[12]
- Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Milik
Hak milik adalah hak turun menurut, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.[13] Hak milik hanya dapat dipunyai oleh WNI.[14] Saat ini Hak Guna Bangunan dapat berdiri di atas Tanah hak milik. Hak Guna Bangunan ini terjadi melalui pemberian hak oleh pemegang hak milik dengan akta yang dihuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.[15] Hak Guna bangunan ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperbarui dengan akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik.[16]
[1] Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
[2] Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
[3] Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
[4] Pasal 37 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
[5] Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
[6] Pasal 2 huruf f Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan.
[7] Prasetya, Dwi Rangga, Hatta Isnaini Wahyu Utomo. 2019, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Berdiri Di Atas Hak Pengelolaan. Jurnal Res Judicata, Vol. 2, No. 2, Oktober, hlm 314.
[8] Septhian Luck Dwi Putra Gode, Dkk. 2023, Analisa Yuridis Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Yang Bisa Dijadikan Jaminan Utang, Jurnal Unes Law Review, Vol. 5, No. 4, Juni 2023, hlm. 3213.
[9] Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
[10] Pasal 15 No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
[11] Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
[12] Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
[13] Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
[14] Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
[15] Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
[16] Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
Dalam Pengadilan Agama terdapat 2 perkara perceraian, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami, sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh isteri.[1]
Cerai gugat dan cerai talak diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Lebih lanjut pengaturan mengenai Cerai talak terdapat dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 72 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam ketentuan tersebut, seorang suami yang hendak menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.[2] Meskipun dalam perkara Cerai Talak menggunakan istilah permohonan, namun perkara ini digolongkan sebagai perkara contentius. Hal ini dikarenakan didalamnya mengandung unsur sengketa dan pemeriksaannya dilakukan dalam proses contradictoir.[3]
Setelah permohonan perkara cerai talak tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim dan memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Ikrar talak adalah pengakuan dan sumpah, mengakhiri atau memutus hubungan/ikatan suami-istri atas kehendak suami dengan kata talak atau sejenisnya.[4]
Lantas apakah pengucapan ikrar talak oleh suami dapat dikuasakan? Dan bagaimanakah pengaturannya?
Terdapat ketentuan “Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak” dalam Pasal 70 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini menyebabkan secara tegas undang-undang memberikan hak bagi pihak pemohon untuk menggunakan kuasa dalam pengucapan ikrar talak. Namun pemberian kuasa pengucapan ikrar talak tidak cukup dengan surat kuasa khusus biasa, melainkan harus menggunakan surat kuasa istimewa yang berbentuk akta otentik. Akta autentik berarti akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.[5] Pada prakteknya penggunaan kuasa istimewa dalam hal pengucapan ikrar talak biasanya berbentuk akta notaris maupun akta yang dibuat dihadapan panitera pengadilan. Di samping harus akta otentik, surat kuasa istimewa tersebut harus bersifat limitatif yaitu terbatas mengenai orang tertentu dan untuk perbuatan tertentu. Redaksionalnya harus secara tegas memberi kuasa untuk mengucapkan ikrar talak.[6]
Berdasarkan penjelasan di atas maka Pemohon cerai talak dapat mengkuasakan ikrar talak dengan menggunakan surat kuasa istimewa yang berbentuk akta otentik dan bersifat limitative.
[1] Muhhamad Ilham, Istilah-Istilah Penting Dalam Berpekara Cerai di Peradilan Agama, https://pa-serui.go.id/istilah-istilah-penting-dalam-berperkara-cerai-di-peradilan-agama/ diakses tanggal 2 Januari 2023
[2] Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
[3] A. Rasyid Roihan. Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali, 1991, hlm .54-55
[4] PA Lubuk Pakam, Sidang Ikrar Talak Melalui Teleconference Antara Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/sidang-ikrar-talak-melalui-teleconference-antara-pengadilan-agama-ujung-tanjung-dengan-pengadilan-agama-lubuk-pakam diakses pada tanggal 2 Januari 2023.
[5] Pasal 1868 KUHPerdata
[6] M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 231.